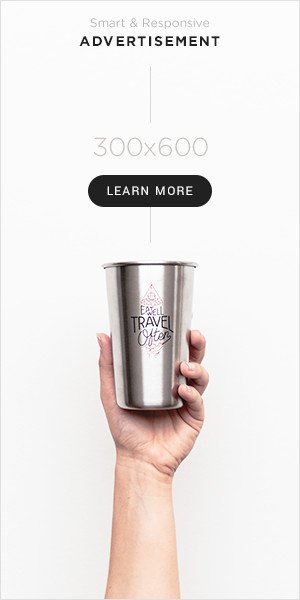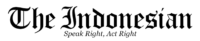theIndonesian – Usai pemilu berakhir, biasanya akan terjadi pembagian kekuasaan. Tujuannya, untuk menciptakan stabilitas politik.
Hal tersebut diungkapkan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Dikutip dari laman Kompas, Kamis (2/5), dia menjelaskan jika ternyata ‘kue’ yang dibagi tidak cukup untuk semua yang meminta jatah, penguasa bisa saja membuat kue menjadi lebih besar.
Dia bilang, “Bagaimana bila jabatan yang bisa dibagikan tak cukup? Jumlah menteri yang diatur dalam undang-undang kementerian negara, sejumlah maksimal 34, bisa saja diubah bila penguasa menginginkannya.”
Perempuan yang juga menjadi pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini pun lalu menyindir soal mengubah hal penting secara tidak etis baru saja dialami bangsa ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan mengenai calon wakil presiden.
Bivitri lalu komentar, “Jangan lupa, ada pula wakil menteri dan menteri koordinator. Tak ketinggalan komisaris badan usaha milik negara.”
Bivitri lalu mengutip Juan Linz (1990), yang menyebutnya consociational democracy atau demokrasi yang dibangun dengan membentuk kerja sama di antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk membagi kekuasaan.
Model ini tidak salah sepanjang dibatasi oleh dua hal. Pertama, peleburan ini tidak boleh meminggirkan aspek akuntabilitas dalam demokrasi dengan tidak membuat koalisi yang terlalu besar.
Kedua, ia harus dibuat dengan visi yang jelas, tujuan bernegara yang terang bagi semua—bukan tanpa arah hanya untuk membagi kekuasaan untuk keuntungan elite politik.
Tidak boleh dilupakan lupakan, negara eksis karena ada warga. Bahkan, penguasa mendapatkan kekuasaannya dari warga.
Kata Bivitri, “Saatnya kita mengkritik pandangan bahwa setelah pemilu dianggap selesai warga cukup menyerahkan urusan politik kepada orang-orang yang sudah dipilihnya. Bila ini yang terjadi, sumber-sumber daya alam Indonesia akan semakin terkuras, untuk kepentingan elite pemegang kekuasaan.”
Bivitri kemudian mengungkapkan bahwa pandangan yang keliru ini sengaja dibiarkan, sementara kesibukan terjadi di sisi sebaliknya, yaitu politikus yang justru sibuk mengorganisasikan kekuasaan.
Tegas dia, “Tapi bila negara hanya organisasi kekuasaan, apa bedanya negara dengan organisasi bajak laut atau mafia, misalnya? Yang membedakan tentu saja hukum; mafia melanggar hukum, sedangkan negara justru dianggap mempunyai legitimasi hukum sebagai kekuasaan yang sah.”
Bivitri kembali tegaskan, “Nyatanya, negara juga bisa melanggar hukum, baik secara kolektif dalam pelanggaran hak asasi manusia maupun dalam kasus perorangan seperti dalam tindak pidana korupsi. Bahkan, negara justru membuat hukum sehingga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ditentukan sendiri oleh negara.”
The Indonesian | Kompas