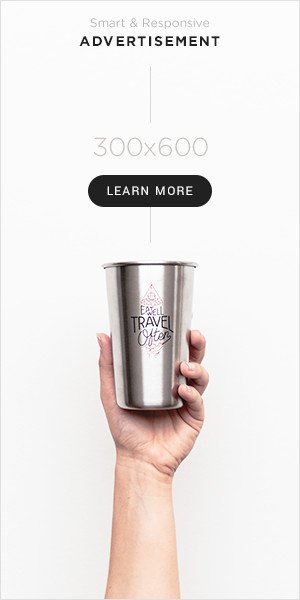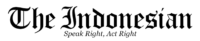‘theindonesian – Ketika negara sedang menunjukkan kekuasaannya dan mengabaikan norma hukum yang berlaku. Intimidasi, kepongahan, dan segala cara dilakukan demi melanggengkan kekuasaan. Maka, negara dan penguasa tersebut sebenarnya sedang tidak menunjukkan kekuatannya.
Sebaliknya, hal itu sebenarnya menunjukkan kelemahan negara dan sang penguasa. Kondisi itu memperlihatkan secara kasat mata bahwa kekuasaan itu sedang dalam keadaan limbung dan mengalami sakit yang serius.
Hampir diseluruh belahan dunia saat ini sebuah negara bercita-cita mengedepankan hukum sebagai panglimanya. Konsep negara hukum pertama kali dilontarkan oleh Plato, lalu pemikiran tersebut kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, sebuah konsep penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik, atau biasa disebut nomoi—undang-undang biasa.
Perkembangannya, seorang guru besar asal Jerman bernama Heinrich Rudolf Hermann Friedrich von Gneist (13 Agustus 1816 – 22 Juli 1895), dalam bukunya yang berjudul Das Englische Verwaltungsrecht (1857) menggunakan istilah rechtsstaat untuk menunjuk sistem hukum yang berlaku di Inggris.

Rudolf von Gneist secara detail membahas rechtsstaat dalam bukunya yang berjudul Der Rechtsstaat. Berkenaan dengan ini Willem van der Vlugt, guru besar di Leiden dalam disertasinya yang berjudul De Rechtsstaat Volgens de Leer van Rudolf von Gneist menyatakan pendapatnya bahwa kepada Gneist-lah seharusnya diberi penghormatan yang tadinya dengan kurang tepat diberikan kepada Montesquieu.
Sebelumnya, seorang cendekiawan hukum tata negara berkebangsaan Inggris, Albert Venn Dicey (4 Februari 1835 – 7 April 1922), menamakan istilah negara hukum dengan nama rule of law. Secara prinsip, rechtsstaat atau rule of law bertujuan membatasi penguasa (pemerintah dalam artian luas) dalam bersikap dan bertindak, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu atas rakyatnya.
Ironi, doktrin rechtsstaat atau rule of law hanya bisa tumbuh di negara yang menganut demokrasi. Tanpa negara hukum dan demokrasi yang hadir hanyalah paham totaliter, fasis, absolut dan represif. Namun, banyak atas nama demokrasi, para penguasa menjalankan kekuasaan secara Machiavellianism (baca: Machiavelli, Antara Ambisi Kekuasaan dan Politik Pengkhianatan), dan mengkhianati sistem demokrasi yang berlaku.
Para penguasa itu menjadikan politik sebagai panglima, dan hukum dijalankan sebagai alat mempertahankan kekuasasaan yang tidak sejalan dengan penguasa. Kondisi seperti ini kemudian dinamakan sebagai negara kekuasaan atau machtsstaat.
Zahermann Armandz Muabezi dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 421-446 berjudul Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) menulis, doktrin negara hukum dan demokrasi sama-sama merupakan atribut negara modern dari sebuah sistem politik yang dibangun lebih dari dua abad yang lalu.
Transformasi transisi demokrasi, tulis Zahermann, memastikan bahwa kekuasaan otoriter menjadi demokrasi berdasar supremasi hukum menyiratkan bahwa keduanya dapat dicapai secara bersamaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang diberi peran masing-masing dan kesempatan secara bersama sesuai kesepakatan yang telah disetujui di awal.
Zahermann mengkritisi dua permasalahan utama, yaitu mengapa negara harus berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (machtsstaat) dan bagaimana pula hubungannya antara negara hukum dan demokrasi?
Penjelasan Zahermann, negara hukum rechtsstaat dan the rule of law merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Perlu diketahui, latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau.
Ide negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Secara embrionik, gagasan negara hukum bermula dari Plato, ketika mengintroduksi konsep nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya.
Gagasan Plato ini didukung oleh Aristoteles dalam bukunya Politica. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dan perumusan yang masih melekat kepada ‘Polis’. Dalam polis segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia), di mana seluruh warga negaranya ikut serta ambil bagian dalam urusan penyelenggaraan negara.
Di satu sisi, meskipun konsep negara hukum menganut konsep universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam.
***
Filsafat hukum membagi aliran negara hukum terdiri dari tiga aliran utama. Pertama, aliran Eropa Kontinental. Kedua, aliran Anglo Saxon, Ketiga, Komisi Juris Internasional. Ketiga aliran ini pada intinya menegaskan bahwa setiap negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membuat keputusan yang dibuatnya.
Melansir buku Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam (2012) tulisan Muhammad Tahir Azhar ada tujuh ciri-ciri negara hukum. Sebut saja pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang (due process of law), supremasi hukum (supremacy of law), kekuasaan peradilan yang independen, peradilan tata usaha negara, dan pemerintahan yang demokratis.
Ketujuh ciri tersebut pada intinya memuat pembatasan kekuasaan serta penghormatan atas hak warga negara. Pembagian kekuasaan dalam konsep negara hukum sangat penting dilakukan. Tujuannya, agar kekuasaan tidak hanya terkonsentrasi pada satu organ, dan seluruh organ negara dapat bekerja sama untuk menciptakan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakatnya.
***
Sudah sejak awal republik ini berdiri, Sukarno sudah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat). Oleh karena itu, hukum menjadi salah satu pilar penting bagi negara ini, dan prinsip ini pada umumnya disepakati oleh presiden, siapa pun di negeri ini.
Ubedillah Badrun, analis sosial politik, dalam tulisannya berjudul Indonesia Machtstaat! di sebuah media daring menulis, sejarah mencatat bahwa sehari setelah Indonesia merdeka, ketika Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) bermusyawarah pada 18 Agustus 1945, mereka sepakat mencantumkan soal bagaimana negara Indonesia dikelola khususnya dalam bagian penjelasan di bagaian sistem pemerintahan negara.

Berdasarkan bagian penjelasan tersebut pada point (1) dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtstaat). Juga dijelaskan secara gamblang bahwa pemerintahan Indonesia itu berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen tahun 2002 juga disebutkan dalam batang tubuh pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi; Negara Indonesia adalah negara hukum.
Sebelumnya, tulis Ubedillah, ada ayat dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu semua menunjukan pentingnya pemimpin yang demokratis karena kedaulatan ada ditangan rakyat (demokrasi) dan taat pada hukum yang telah disepakati bersama (rechtstaat).
Hal itu menggambarkan spirit awal yang jelas bagaimana republik Indonesia berdiri dan seharusnya dijalankan. Sejak awal Indonesia merdeka melalui perdebatan intelektual yang mencerahkan di BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) maupun di PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 akhirnya sepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik.
Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Penjelasan Ubedillah, konsep negara republik dipilih karena secara sadar para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara modern yang dikelola dengan cara-cara modern, mendengarkan aspirasi rakyat banyak termasuk cara-cara memilih pemimpinnya yang tidak dilakukan secara turun menurun (monarki) tetapi melalui musyawarah dan mendengarkan aspirasi rakyat.
“Itulah spirit Republikanisme, spirit mentaati konstitusi (rechtstaat), spirit menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, spirit pembatasan kekuasaan, spirit demokrasi deliberatif (Johm Milton, Aeropagitica, 1644),” tulis Ubedillah.

Foto: Istimewa.
Dia menambahkan, dengan merujuk pada awal pembentukan negara dan perspektif republikanisme, bisa disimpulkan bahwa Indonesia saat ini sesungguhnya memasuki episode machtstaat (negara kekuasaan) yang sangat membahayakan masa depan Indonesia sebagai republik.
Pertanyaannya, kok bisa Indonesia menjadi machtstaat atau negara kekuasaan? Secara empirik para ilmuwan dan akademisi ilmu sosial politik dan hukum yang masih independen dalam keilmuanya pada umumnya memberikan kesimpulan yang sama bahwa Indonesia pernah menjadi machstaat dan kini memasuki episode machtstaat yang paling membahayakan masa depan Indonesia sebagai negara republik.
Ubedillah mengungkapkan, ada tiga episode Indonesia menjadi machtstaat. Pertama, episode machtstaat era Sukarno. Kedua, episode machstaat era Soeharto. Ketiga, episode machtstaat era Jokowi.
Pada era Sukarno terjadi sekitar tujuh tahun di akhir kekuasaanya dari 1959 hingga 1966. Di era ini, negara kekuasaan (machtstaat) sangat terlihat sejak dekrit Presiden 5 Juli 1959, kemudian Sukarno membubarkan parlemen hasil pemilu dan mengangkat anggota DPR-GR (1960), membubarkan Partai Masyumi dan PSI (1960), menerima diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS (1963), membubarkan Partai Murba (1965) dan seterusnya hingga kekuasaanya jatuh pada 1967.
Pada era Soeharto, machtstaat terjadi secara sistemik sejak dikeluarkanya lima paket undang-undang politik pada 1985. Sejak keluarnya paket undang-undang politik itulah kekuasaan Soeharto semakin kuat mengendalikan seluruh kekuatan politik (DPR/MPR, partai, ormas, dll), dan dipenghujung kekuasaanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin subur hingga jatuh pada 1998.

Pada era Jokowi, ungkap Ubedillah, machtstaat terjadi sejak 2019 ketika presiden bersama DPR tidak mau mendengarkan aspirasi ratusan ribu rakyat, mahasiswa, akademisi, para aktivis, buruh dan lainnya yang menolak revisi UU KPK hingga disahkan pada 17 September 2019.
Melalui revisi UU KPK itulah KPK kini menjadi tidak independen lagi karena menjadi bagian dari lembaga eksekutif di bawah kendali presiden. Disaat yang sama KKN masih terus merajalela.
Negara kekuasaan juga terlihat ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu No 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi UU 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan. UU ini membuat presiden memiliki kewenangan yang absolut karena sepanjang tiga tahun (2020-2022) presiden dapat mengeluarkan APBN hanya berdasar peraturan presiden (perpres).
Selain itu, keputusan yang didasari UU No.2 tahun 2020 ini tidak bisa menjadi obyek gugatan yang dapat diperkarakan di PTUN. Checks and balances hilang, apalagi koalisi pemerintah menguasai 80 persen lebih suara parlemen. Negara kekuasaan juga semakin terlihat ketika pemerintah dan DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat yang menolak pengesahan Omnibuslaw UU Cipta kerja tahun 2020.
DPR akhirnya mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Sebagai informasi, UU Cipta Kerja ini dibuat atas inisiaif Presiden Jokowi, ada 79 undang-undang yang diringkas. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 memutuskan bahwa Omnibuslaw UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak konstitusional atau inkonstitusional bersyarat.
Enam bulan kemudian DPR mengesahkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) pada 5 Mei 2022. UU P3 ini yang menjadi landasan hukum atau semacam perlindungan hukum perbaikan UU Cipta Kerja.
Indonesia kini semakin menjadi machtstaat karena intervensi kekuasaan tidak hanya terhadap legislatif tetapi juga pada lembaga yudikatif seperti terhadap MK, misalnya dalam kasus pemberhentian Aswanto seorang hakim MK yang diganti karena dinilai DPR Aswanto gagal mengamankan produk hukum yang dibuat DPR bersama pemerintah.

Foto: Istimewa.
Padahal MK itu wilayah yudikatif yang kemerdekaan kewenangannya dijamin konstitusi UUD 1945 untuk menguji suatau undang-undang produk DPR. Celakanya, presiden dengan senang hati melantik Guntur Hamzah pengganti Aswanto menjadi hakim MK.
Terbaru, ketika sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Senin, 16 Oktober 2023, terkait putusan uji materiil pasal 169 huruf q UU Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Penilaian machtstaat kembali muncul karena putusan MK tersebut memberi ruang bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres saat bapaknya, Joko Widodo, masih menjabat dan berkuasa sebagai presiden pada waktu pemilihan, yaitu 14 Februari 2024.
Versi Ubedillah, mengapa episode machtstaat era Jokowi ini paling membahayakan masa depan republik? Jawabanya rezim ini tidak hanya mengendalikan lembaga legislatif hingga hilang checks and balances-nya tetapi juga mengendalikan lembaga yudikatif.
Lebih berbahayanya, negara kekuasaan yang bersekongkol dengan oligarki ini telah menyusup dan merusak ke dalam lebih dari 80 UU hanya dalam waktu tiga tahun kekuasaanya di periode kedua ini.
“Pada akhirnya negara hukum (rechstaat) yang demokratis yang merupakan spirit utama negara republik yang dicita-citakan para pendiiri bangsa ini kini secara sistemik telah dirampas oleh machtstaat yang dijalankan pada episode Presiden Jokowi ini,” tulis Ubedillah.
Pertanyaannya kemudian, apakah publik saat ini masih menilai bahwa republik ini menganut sistem rechtsstaats atau memang telah menjelma menjadi machtsstaat? Kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia sendiri yang bisa menilainya.
(TheIndonesian)