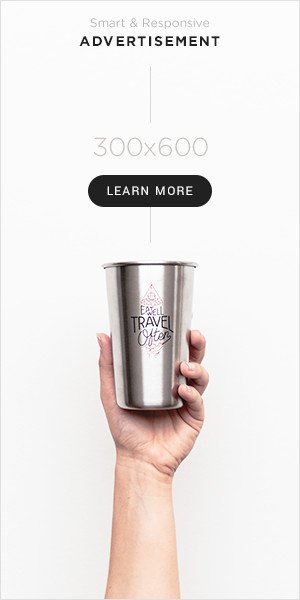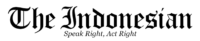theIndonesian – Tragedi nasional pada 1965 membawa banyak korban pada rakyat, baik berbagai pihak yang dianggap terkait dengan Gerakan 30 September (G308) maupun keluarganya.
Cribb R dalam buku How Many Death? menulis, diperkirakan korban meninggal mencapai setengah juta orang selama enam bulan setelah G30S. Banyak analisis disusun untuk menjelaskan latar belakang meletusnya tragedi 1965.
Sementara, Soebandrio mengungkapkan di dalam bukunya yang berjudul Yang Saya Alami Peristiwa G 30S, merefleksikan peristiwa itu dalam kaitan konstalasi internasional sebagai penghancuran PKI yang diikuti pembunuhan jutaan manusia mendapat dukungan kekuatan imprealisme internasional, terutama Amerika Serikat yang mengklaim sebagai negara demokrasi.
“Ini bentuk penghancuran struktur di suatu negara (Indonesia) yang sangat besar sejak Perang Dunia II. Kekejamannya tidak pernah dibayangkan sebelumnya, oleh siapa pun, termasuk oleh kita sendiri, juga termasuk saya,” tulis Soebandrio.
H Purwanta dari jurusan sejarah Universitas Sanata Dhanna Yogyakarta di dalam tulisannya yang berjudul Gerakan Kiri di Klaten: 1950 – 1965 di dalam buku Patrawidya, Seri Penerbitan Penelitian Sejaran dan Budaya (2012) menceritakan, selain meninggalkan luka yang mendalam, tragedi 1965 juga meninggalkan pertanyaanpertanyaan yang menarik untuk dikaji.
Misalnya, terkait pembantaian yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menurut Purwanta, Kabupaten Klaten merupakan salah satu ladang pembantaian ‘orang-orang kiri’ dari daerah segitiga yang terkenal, bersama Solo dan Boyolali. Di ketiga daerah tersebut ribuan orang dibunuh, dihukum dan ditahan atas nama Gerakan Pemberantasan PKI dan antek-anteknya.
Khusus untuk wilayah Kabupaten Klaten, terdapat berbagai tempat yang diyakini sebagai lokasi pembunuhan massal dan meski tinggal sedikit, masih terdapat orang-orang yang dahulu ditahan, dihukum, bahkan di ‘Pulau Buru’-kan.
“Tak terelakkan, di mana-mana terjadi aksi balas dendam terhadap PKI atau mereka yang dicurigai simpatisan PKI. Pembantaian besar-besaran pun tak bisa dibendung. Walaupun, tidak sedikit korban fitnah, lalu dihabisi tanpa diberi kesempatan membela diri,” tulis buku tersebut.
Tidak hanya itu, di kalangan militer setingkat Kodim kala itu, ada semacam pemberian hadiah bagi anggota militer yang bisa membunuh orang atau simpatisan PKI. Makin banyak yang dibunuh, seorang anggota militer makin cepat naik pangkat.
Maka tidak heran, jika di tepi Kali Wedi, Klaten, misalnya, setiap hari dijumpai pemandangan mengerikan; pembantaian manusia. Tidak jarang orang satu kampung digiring, lalu dibantai ramai-ramai di tepi kali.
“Ini cerita sungguhan bukan fiktif,” ungkap Subandyo, dikutip dari buku Mendamaikan Sejarah: Analisis Wacana Pencabutan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang ditulis Kasemin.
***
Sejarah bercerita. Salah satu permasalahan kronis di Klaten adalah persoalan agraria. Semenjak perjanjian Giyanti tahun 1755, Kabupaten Klaten menjadi bagian wilayah Kerajaan Kasunanan Surakarta yang dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda dikategorikan sebagai daerah vorstenlanden.
Seperti daerah vorstenlanden lainnya di Jawa, Kasunanan Surakarta merupakan kerajaan agraris, yaitu kerajaan yang bertumpu pada pertanian sebagai basis kehidupan hampir seluruh penduduknya.
Padmo S, dalam buku Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten: 1959 1965, menulis, ketika pengusaha Barat masuk ke pedesaan Jawa, Kabupaten Klaten menjadi salah satu wilayah yang menjadi objek.
Sebagai bagian wilayah kerajaan, pengusaha swasta tidak menyewa langsung kepada rakyat, tetapi melakukan kontrak dengan para bangsawan pemilik lungguh (patuh).
Tulis Padmo, pola kontrak melalui bangsawan pemilik tanah lungguh mengakibatkan rakyat petani tidak memperoleh keuntungan terhadap masuknya perusahaan Barat di wilayah mereka. Bahkan sebaliknya, petani justru mengalami kerugian dan penderitaan.
Padmo lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan usahanya, para pekebun secara intensif telah memanfaatkan ratusan ribu hektare tanah di pegunungan untuk mengusahakan tanaman keras seperti teh, karet, dan kopi dengan melibatkan wong cilik yang ada di desa sekitarnya.
Apabila tenaga kerja tidak tersedia di desa sekitar, maka tenaga kerja itu harus didatangkan dari desa yang berjarak 7-10 kilometer secara periodik. Tidak jarang penduduk pedesaan (wong cilik) selama puluhan tahun dipaksa melaksanakan kerja wajib itu lahir, hidup, dan mati di kebun kopi.
Para petani di daerah persawahan yang subur dipaksa untuk menanam tebu, tembakau, dan nila dalam kerja wajib. Salah satu sumber penderitaan rakyat selama penyewaan tanah oleh perusahaan perkebunan Barat adalah sistem glebagan, yaitu sistem pengolahan tanah secara bergantian.
Tanah garapan rakyat dibagi menjadi dua. Misalnya untuk tahun pertama dikerjakan persil A, musim penanaman selanjutnya berpindah ke persil B bekas yang ditanami. Sistem glebagan mengakibatkan tanah garapan petani berkurang setengahnya, karena ditanami tanaman perdagangan (cash crop) oleh pengusaha Barat, seperti tembakau, tebu atau nila.
Apabila diambil rata-rata, di daerah Klaten, di bagian tanah yang sangat subur, tanah garapan petani rata-rata hanya 1/3 bau, atau kurang dari 1,4 hektare. Di bagian yang tidak subur agak sedikit lebih luas.
Situasi ini menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah yang memiliki potensi besar bagi terjadinya konflik kepemilikan lahan pertanian. Kemiskinan struktural masyarakat Kasunanan Surakarta pada umumnya dan Kabupaten Klaten khususnya menjadi potensi yang mampu menumbuhkembangkan gerakan kiri pada masa kemerdekaan.
Salah satu ekspresi gerakan kiri di masa awal kemerdekaan adalah penentangan terhadap kekuasaan Kasunanan Surakarta dalam bentuk Gerakan Anti Swapraja. Gerakan itu dipelopori oleh kaum kiri pimpinan Tan Malaka.
Dia menuliskan rancangan program ekonomi untuk kaum proletar di Indonesia. Misalnya, membagi-bagikan tanah yang kosong kepada tani yang tak bertanah dan miskin dengan memberikan sokongan uang untuk mengusahakan tanah itu. Lalu, menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada tani-tani yang miskin.
***
Pengaruh Gerakan Anti Swapraja semakin lama semakin meluas. Pada awalnya sasaran utamanya adalah lingkup pusat pemerintahan istana kerajaan, seperti penculikan dan pembunuhan Patih Kasunanan Surakarta KRMH Sosrodiningrat, pada 17 Oktober 1945.
Selanjutnya, pengaruh Gerakan Anti Swapraja berkembang ke tingkat kabupaten. Hal itu antara lain terlihat dari penculikan dan pembunuhan para bupati seperti yang terjadi di Klaten (RT Pringgonegoro) dan Boyolali (KRT Reksonegoro).
Guna mengatasi situasi yang semakin tidak terkendali, pemerintah pusat kemudian mengakhiri Daerah Istimewa Surakarta pada 16 Juni 1946 dan menggantinya dengan status sebagai Karesidenan Surakarta.
Kesuksesan menjatuhkan kekuasaan aristokratis Kasunanan Surakarta menjadikan gerakan kiri semakin percaya diri untuk tetap membela kepentingan rakyat kecil. Bahkan pemerintah pada 26 April 1948 menandatangani Undang-Undang No 13 yang diberi judul Undang-Undang Perubahan Vorstenlandsch Grondhuurreglement.
UU itu menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki semangat untuk menyejahterakan rakyat, khususnya petani. Di sisi lain, pemerintah juga melihat bahwa Vorstenlandsch Grondhuurreglement mengandung banyak ketidakadilan bagi petani.
Purwanta menulis, kepercayaan diri para aktivis gerakan kiri di Surakarta pada umumnya dan kabupaten pada khususnya tampak dari meletusnya pemogokan buruh Badan Tektil Negara (BTN) di Delanggu pada 19 Mei 1948.
Dalam rangka melakukan perundingan dan negosiasi dengan direksi BTN, buruh dan petani bersatu dalam Lembaga Buruh Tani (LBT). Dalam siaran pers yang dimuat pada surat kabar Suara Ibu Kota, 21 Mei 1948, dan dikutip dalam Arsip Kementerian Penerangan No 242 dijelaskan, aksi ini bukan saja dilakukan oleh Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) saja, sebab banyak kaum tani kecil turut berburuh pada perusahaan-perusahaan BTN.
Nasib mereka dan anggota-anggota Sarbupri sama. Kali ini buruh dan tani menghadapi satu majikan. Perselisian antara Sarbupri dan Dewan Pimpinan BTN sudah berjalan lama, sekitar tujuh bulan. Selama waktu itu para majikan tidak pernah menunjukkan niat baiknya.
Upah pekerja yang diizinkan oleh BTN sebesar Rp 2 sehari dengan kupon beras 200 gram yang harus dibeli seharga Rp 1,5 per kg. Dibandingkan dengan upah buruh tani di luar kebun dari Rp 10 hingga Rp 15, maka upah BTN sangat tidak menarik rakyat.
Pemogokan berlangsung secara bergelombang dan baru sepenuhnya berakhir pada 17 Juni 1948 yang ditandai oleh keluarnya perintah dari Biro Sentral Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) kepada Sarbupri dan Barisan Tani Indonesia (BTI) di Delanggu supaya mulai pada Ahad, 18 Juli 1948 pukul 07.00 segenap buruh dan buruh tani di daerah tersebut bekerja seperti biasa.
Keberhasilan dalam memperjuangkan nasib melalui pemogokan pada 19 Mei – 17 Juni 1948 memberi harapan baru bagi petani miskin untuk mengubah nasib mereka. Keberhasilan itu tidak dapat dipungkiri berkat bantuan dan dukungan para aktivis gerakan kiri, baik yang bernaung pada organisasi sosial maupun partai politik. Oleh karena itu menjadi wajar apabila pada 1950-an banyak aktivis dari Kabupaten Klaten berafiliasi dengan gerakan kiri nasional, baik sebagai anggota maupun simpatisan.
***
Pada Pemilihan Umum 1955, untuk daerah pemilihan Kabupaten Klaten, Partai Komunis Indonesia (PKI) memperoleh 204.869 suara, sedang Partai Nasional Indonesia (PNI) sebanyak 109.667 suara dan Partai Masyumi 48.530 suara, sebagai mana ditulis di dalam Politiek en Cultuur, sebuah jurnal bulanan edisi Desember 1955 yang diterbitkan di Amsterdam, Belanda.
Kemenangan PKI yang hampir dua kali lipat dari PNI dengan sangat jelas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Klaten menaruh harapan kepadanya. Dominasi golongan kiri di Kabupaten Klaten tidak hanya pada isu-isu politik nasional, tetapi juga pada kegiatan sosial dan kebudayaan di tingkat loka.
Organisasi-organisasi pemuda, pelajar dan kesenian yang berafiliasi dengan PKI juga berkembang dengan pesat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Semua kecamatan memiliki cabang dari Pemuda Rakyat (PR), Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).
Melalui komunikasi lisan antarteman dan tetangga, para pelajar dan pemuda direkrut menjadi anggota organisasi dan ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya. Agustinus Mulyono, yang pemah menjabat sebagai ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Kecamatan Wedi menjelaskan, perekrutan anggota dilakukan dengan sistem jawilan untuk diajak ikut pertemuan.
Melalui keikutsertaan pada pertemuan-pertemuan itu, secara alamiah akan tersaring siapa saja yang tertarik dan bersedia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan IPPI serta siapa saja yang tidak tertarik. Kegiatan organisasi gerakan kiri yang menjadi underbouw atau berafiliasi dengan PKI memang beragam dan menjadi daya tarik sendiri bagi anggota masyarakat untuk melibatkan diri.
IPPI yang ditujukan untuk pelajar SMP dan SMA, memiliki kegiatan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akademik dan non akademik. Dalam bidang akademik, IPPI mengembangkan kelompok-kelompok belajar, sehingga terjadi saling belajar antarteman. Melalui belajar bersama, berbagai kendala akademik, seperti keterbatasan sumber belajar, kekurangpahaman terhadap materi belajar dapat diatasi.
Selain itu, kegiatan ini dipandang sangat penting, terutama ketika terjadi persaingan prestasi akademik dengan organisasi sejenis dari kelompok lain, seperti dari Partai Katholik, Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia.
***
Memasuki periode 1960-an, pada periode ini aktivitas gerakan kiri di Klaten meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Ditinjau dari sasarannya, aktivitas gerakan kiri dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perusahaan perkebunan, kelompok masyarakat yang oleh DN Aidit disebut sebagai ‘setan desa’, serta pimpinan pemerintahan, khususnya Bupati Klaten M Pratikto.
Kepada perusahaan perkebunan, aktivis gerakan kiri menuntut dilibatkannya petani pemilik lahan dalam musyawarah sewa tanah, sehingga memperoleh harga yang adil. Permasalahan utama dalam persewaan lahan pertanian oleh pabrik atau perusahaan perkebunan adalah kurang dilibatkannya petani pemilik sawah.
Seperti zaman penjajahan, perjanjian sewa menyewa dilakukan antara pabrik dengan pamong desa. Perbedaannya, kalau dahulu dengan sistem glebagan, sekarang menggunakan sistem walik lubang.
Dalam sistem yang baru, perusahaan perkebunan menyewa tanah di suatu areal secara tetap dan hanya mengolahnya lagi setelah panen dilakukan. Problem lain yang diangkat oleh aktivis gerakan kiri adalah murahnya harga sewa apabila dibandingkan dengan hasil panen saat ditanami sendiri oleh petani.
Suto Sandi sebagai salah satu eksponen BTl bersikeras menentang sewah tanah untuk tanaman tebu ditentukan oleh kelurahan. Aktivitas gerakan kiri Klaten pada 1960-an yang terlihat semakin keras bukan tanpa alasan.
Dari perspektif para aktivis gerakan kiri, kekerasan itu muncul karena musyawarah mengalami kebuntuan, terutama terkait dengan pelaksanaan berbagai UU dan peraturan pemerintah yang telah diundangkan pada 1960.
Para aktivis gerakan kiri menuntut berbagai peraturan itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi berbagai pihak di Klaten dipandang justru menghambat. Salah satu undang-undang yang dituntutkan oleh gerakan kiri adalah UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU PBH).
UU itu disusun dengan tujuan antara lain, agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil. Kemudian, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap.
Lalu, dengan terselenggaranya apa yang tersebut di atas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani-penggarap. Hal itu akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanah.
Klaten memang menyimpan sejarah kelam. Sebut saja Sungai Pandansimping di perbatasan Kecamatan Jogonalan dan Prambanan, Klaten. Sungai ini punya sejarah horor yang dipercaya sebagai tempat kuburan massal. Di sungai itu ratusan bahkan disebut hingga seribuan orang tahanan PKI dieksekusi pada 1965.
Belum lagi soal kisah seorang kiai bernama Tartibi pada era 1960-an asal Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Klaten yang tega dihabisi PKI. Tartibi merupakan seorang ulama yang berasal dari Kampung Babat, Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk. Kiai Tartibi dihabisi PKI dengan menindih kepalanya hingga hancur.
Lalu, pascameletusnya G30S PKI, terjadi peristiwa kelam di Kabupaten Klaten yang dikenal sebagai Kentong Gobyok 1965. Konflik, sabotase, penculikan dan pembunuhan beraroma rivalitas politik itu terjadi pada Oktober 1965. Pohon-pohon di tepi jalan raya ditebangi. Mulai dari Tegalgondo sampai Delanggu.
Sejarah kelam di Kabupaten Klaten tak boleh berulang kembali. Namun, ketika ketidakadilan terus dipaksakan, kesewenangan dilakukan membabi buta, dan arogansi kekuasaan terus ditunjukkan, ingatlah selalu bahwa daerah ini memiliki sejarah perlawanan yang panjang akan kekuasaan yang tiran.
(TheIndonesian).