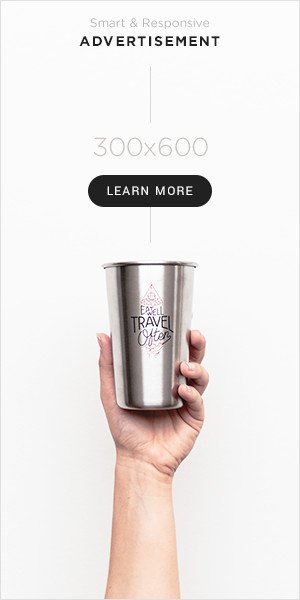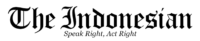theIndonesian – Banjir! Kata itu sudah tidak asing lagi bagi warga Jakarta yang tinggal dipinggiran bantaran kali. Jakarta sejak dulu tercatat menjadi langganan air bah (banjir). Kawasan di muara Kali Ciliwung awalnya merupakan dataran rendah alluvial, hasil pengendapan lumpur dari pegunungan.
Selain itu, banyaknya rawa-rawa di daerah Jakarta pada saat itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Menurut sejarah, orang-orang Belanda yang pertama kali singgah di akhir abad ke-17 menceritakan, di sekitar daerah kota pelabuhan (Sunda Kelapa) itu terdapat tanah-tanah yang tergenang air.
Banjir di daerah muara Ciliwung itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Purnawarman. Raja Tarumanegara yang berkuasa pada saat itu akhirnya memerintahkan penggalian Kali Candrabaga dan Gomati (mungkin terletak di Bekasi, red) untuk mencegah banjir.
Selain Ciliwung, masih ada sejumlah sungai lain yang melintasi daerah Sunda Kelapa. Misalnya Kali Angke, Kali Krukut dan Kali Grogol di bagian barat. Sedang di bagian timur ada Kali Sunter dan Kali Gunung Sahari.
Setelah Betawi (Jakarta) dikuasai Kompeni (Belanda), ancaman banjir makin menjadi-jadi. Kompeni yang membangun kastil tidak memahami kondisi alam di Betawi. Karena ingin membangun kota seperti di negara asalnya, Nederland, para pembesar Kompeni meluruskan Kali Ciliwung serta membuat kanal-kanal atau kali buatan. Karena faktor sedimentasi Ciliwung sangat tinggi, kali-kali itu cepat dangkal karena endapan lumpur, dan akibatnya ketika hujan turun, terjadilah banjir. Dan itu terus terjadi hingga sekarang.
Jakarta pertama kali dikenal sebagai pelabuhan di muara Sungai Ciliwung. Asal-usulnya bisa ditelusuri dari zaman Hindu pada abad ke-5. Orang Eropa pertama yang datang ke Jakarta adalah orang Portugis. Pada abad ke-16, para pendatang Portugis diberi izin mendirikan benteng di Sunda Kelapa.
Asal-usul hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni adalah penaklukan Sunda Kelapa oleh Fatahillah pada tahun 1527 dan mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan.
Kemudian, orang Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16 dan pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen menaklukan Jayakarta dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Dalam masa Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting.
Penjajahan yang dilakukan oleh Jepang pada 1942 kemudian mengganti nama Batavia menjadi Jakarta. Tujuannya adalah, untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Uniknya, sekitar tahun 1720, pabrik-pabrik gula cukup banyak didirikan di sepanjang Sungai Ciliwung. Dari sejumlah 130 pabrik terdapat 50 pabrik gula yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Para pekerja biasa membuang sisa-sisa sampah tebu ke Sungai Ciliwung. Mereka tidak menyadari bahwa akibat kebiasaannya itu aliran sungai menjadi tersumbat.
Kini, persoalan banjir kerap menjadi momok siapa pun yang menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Sejumlah cara penanganan banjir telah dijalankan. Anggaran yang digelontorkan untuk menangani banjir pun tidak sedikit. Ironinya, bencana banjir di Jakarta justru juga dijadikan ajang komoditas politik.
Tokoh nasional asli warga Betawi, Muhammad Husni Thamrin atau MH Thamrin (16 Februari 1894 – 11 Januari 1941) pernah terlibat dalam penanganan masalah banjir di kota ini. MH Thamrin adalah politisi era Hindia Belanda yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia.
Batavia, nama yang diberikan Belanda sebelum menjadi Jakarta, pernah mengalamo banjir besar pada 1918. Saat itu mayoritas wilayah Batavia kebanjiran, bahkan istana Gubernur Jendral tak luput dari banjir.
Uniknya, Pemerintah Hindia Belanda kala itu enggan menangani banjir di wilayah rakyat biasa. Belanda hanya ingin penanganan banjir, khususnya di kawasan elite dan hunian warga Belanda di Menteng dan sekitarnya.
Herman van Breen, arsitek Belanda, sebenarnya telah memberikan solusi penyelesaian banjir secara menyeluruh lewat peta kanal banjir pada 1920. Peta kanal banjir ini dibuat bukan hanya untuk kawasan elite Belanda di Menteng, melainkan juga sampai ke Kali Mokervart di Tangerang dan terus mengalirkan banjir ke laut. Namun, usulan itu tidak dipakai oleh Pemerintah Belanda.
JJ Rizal, sejarawan Jakarta, pernah bercerita, saat banjir besar pada 1918, pemerintah Belanda berpikir bahwa hanya kawasan elite hunian Belanda di Menteng saja yang harus selamat dari banjir. Ketika MH Thamrin bergabung di Gemeente (Dewan kota atau DPRD kini) pada 1919, pria lulusan dari Gymnasium Koning Willem III School te Batavia ini turut serta menyuarakan perjuangan rakyat kecil yang kerap dirugikan dengan kebijakan Belanda.
Kala itu, Belanda hanya menyetujui van Breen membuat kanal banjir di kawasan Menteng. “Jadi, wajar kalau sekarang lihat, ada kanal banjirnya sampai di Menteng doang,” kata JJ Rizal, beberapa waktu lalu. JJ Rizal bercerita, ketika kanal banjir di Menteng selesai pada 1922, terjadi banjir besar selanjutnya 1924 di Batavia. Pada banjir 1924, banjir kanal di Menteng tidak berpengaruh sama sekali.
Dikarenakan hampir semua kawasan Batavia tetap tergenang banjir, tidak terkecuali Menteng, maka pada 1924 kanal banjir ini sudah tidak berguna sama sekali. Van Breen lantas melakukan evaluasi. Dia menyadari penyelesaian banjir di Batavia tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan infrastruktur. “Dari sini van Breen banyak belajar dari Thamrin, sebagai orang asli Betawi dan orang Kampung,” kata JJ Rizal.
Cerita berlanjut. MH Thamrin yang biasa mandi di kali dan beraktivitas di sungai, menyadari wilayah Batavia selalu terkait dengan nama-nama tempat yang selalu terkait dengan air, tanaman, dan buah-buahan.
Ini kemudian menginspirasi van Breen, di mana pendekatan alam dan manusia tidak kalah penting. MH Thamrin menginspirasi van Breen bahwa perlu ada kawasan hijau di banyak tempat di bantaran sungai dan situ-situ di Batavia.
“Tempat-tempat ini harus dikasih ‘cincin’ ruang hijau, terutama kawasan ‘cincin hijau’ yang besar ada di kawasan selatan Jakarta, dari Pasar Minggu sampai ke Puncak,” cerita dia. JJ Rizal melanjutkan, sayangnya ketika ide itu sedang gencar diperjuangkan di Gemeente dan Volksraad (Dewan Rakyat/DPR), Pemerintah Belanda justru memberi izin swasta lahan Batavia.
Lahan itu digunakan untuk kebun teh. Maka marah besarlah MH Thamrin di Volksraad karena Pemerintah Belanda memberi izin pembukaan lahan perkebunan di selatan Batavia. “Thamrin pun meminta swasta pemilik kebun teh membayar cukai lebih tinggi karena akibat buruk kerusakan lingkungan di Batavia,” ujar Rizal.
MH Thamrin dan van Breen, ucap Rizal, sejak berabad lalu telah membayangkan bahwa sebuah kota masa depan Jakarta itu hanya bisa diselamatkan oleh dua hal. Pertama, menjadi jadi kota hijau. Kedua, sekaligus menjadi kota biru. Maksudnya, kota hijau itu dengan memperbanyak area pepohonan dan terbuka hijau, sedangkan kota biru itu menata tempat penampungan air.
Kini, apakah Pemerintah Kota DKI Jakarta akan mengikuti kembali jejak MH Thamrin dan van Breen untuk mengatasi banjir? Atau memang banjir akan tetap menjadi masalah tanpa solusi karena bisa dengan mudah dijadikan ajang jualan politik bagi para politikus.
(TheIndonesian)